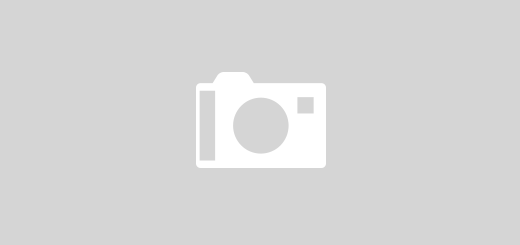Indonesia Butuh Perppu Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Pabrik kembang api-petasan di Tangerang, yang konon baru beroperasi dua bulan meledak, Kamis (26/10). Tiga hari berlalu, kantong-kantong mayat yang telah dibawa ke RS Polri Kramatjati, belum seluruhnya selesai di identifikasi. Sedikitnya 47 korban meninggal dan 31 lainnya luka-luka dari total 103 tenaga kerja PT Panca Buana Cahaya.
Di hari yang sama, di Medan, satu korban meregang nyawa akibat tertimpa besi penyangga proyek kereta Medan-Kualanamu (GoSumut.com). Hari Minggu (29/10) seorang pekerja tertimpa Girder Flyover proyek tol Pasuruan-Probolinggo. Selang lima hari sebelumnya, seorang pekerja pelabuhan di Jakarta juga meninggal dengan sobekan di dada akibat sabetan wayer trolly Container Crane (CC).
Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, sampai Juni 2017 ada 147 pekerja tewas dari 11.028 kasus kecelakaan kerja. Data ini jauh berbeda dari yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja. Ambil contoh misalnya dari data BPJS Tenaga Kerja Cabang Pontianak yang sampai pada Oktober 2017 mengaku sudah mengeluarkan klaim jaminan kematian (JKK) untuk 246 peserta.
Meily Kurniawidjaja, M. Sc, Sp.OK dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar FKM UI, pada tahun 2014, mengatakan bahwa data yang ada di Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) hanya menunjukkan 10% dari kondisi aktual yang sesungguhnya terjadi. Hal ini terkait dengan kondisi bahwa tidak semua pekerja menjadi anggota Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang bersifat informal dan non-formal.
Dalam peristiwa-peristiwa kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian apalagi yang jumlahnya banyak selalu saja aparat yang semestinya bekerja di awal baru heboh belakangan. Saling lempar kewenangan, saling menyalahkan data, saling lempar tanggung jawab, dan akhirnya keluarga korban makin merana. Keluarga korban dijanjikan banyak hal disaat liputan media begitu besar, namun begitu mereda, dibiarkan kebingungan mengurus janji yang terlanjur dilontarkan.
Reda pemberitaan peristiwa kecelakaan kerja yang merenggut nyawa, seolah sudah selesailah kerja yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan. Data tidak diperbaiki, sistem dibiarkan sama, pengawasan kembali “sesuai standar,” paling maksimal akan berakhir pada pengajuan anggaran baru demi perbaikan katanya. Apesnya data yang simpang siur ini juga lah yang menjadi dasar perhitungan pengajuan anggaran.
Kelemahan Peraturan
Sampai 2005 setidaknya ada 48 peraturan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Mulai dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 hingga peraturan-peraturan pelaksana yang dikeluarkan Kementerian dan Lembaga. Ada pembaharuan-pembaharuan memang di peraturan-peraturan pelaksana. Demikian juga tambahan peraturan mengikuti perkembangan industri. Namun Undang-undang Keselamatan Kerja yang hanya berisi 18 Pasal ini masih UU lama yang tidak pernah tersentuh perbaikan.
Pasal 15 UU 1 Tahun 1970 di ayat satu misalnya, menyebutkan “Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Pada pasal 7 Undang-undang yang sama ada ketentuan soal retribusi yang harus dibayar oleh pengusaha dan ini harus diatur dengan undang-undang. Kemudian di pasal 8 (3) Undang-undang ini juga meminta pengaturan UU berkenaan dengan pengujian kesehatan. Selanjutnya pada pasal 11, peraturan ini mensyaratkan wajib lapor kecelakaan kerja diatur dengan perundangan.
Baru pada tahun 1981 ada UU tentan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang pada pasal enam menyebutkan kewajiban pengusaha melaporkan perlindungan tenaga kerja. UU Nomor 7 Tahun 1981 ini sendiri dicantelkan pada UU 14/1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dan tidak sama sekali mencantumkan UU 1/1970 dalam diktum “mengingat.”
Kita baru punya undang-undang yang secara tegas mencantelkan pijakannya pada UU 1/1970 pada tahun 1992. UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menjadi dasar pembentukan PT Jamsostek yang kini sudah dilikuidasi menjadi BPJS (Ketenagakerjaan) melalui UU Nomor 24 Tahun 2011. Bahkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak menyebut sama sekali pertimbangan UU 1 Tahun 1970 walaupun juga berarti tidak serta merta mendelegitimasi pemberlakuan UU Keselamatan Kerja.
Berkenaan dengan manajemen Kesehatan dan keselamatan Kerja, atau “Pengurus” dalam istilah UU Keselamatan Kerja, baru ada pengaturannya secara resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Butuh waktu 9 tahun untuk membuat pengaturan yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sedikit lebih baik dari UU Nomor 3 Tahun 1992 yang butuh 22 tahun untuk mengejawantahkan amanat UU 1 Tahun 1970.
Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1970 ada 3 Peraturan Pemerintah yang langsung lahir tidak berselang lama. PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawsan atas Peradaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida, PP Nomor 19 tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan, dan PP No.11 Tahun 1973 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Di era Reformasi PP Nomor 50 Tahun 2012 lah yang lahir dengan semangat penerapan UU K3 walaupun dalam diktumnya hanya menggunakan cantelan UUK No.13 Tahun 2003.
Harus diakui memang banyak Peraturan Menteri yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Jika merujuk pada daftar periksa pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan, setidaknya ada 15 peraturan yang telah lahir. Mulai dari pengawasan pesawat uap, bejana bertekanan, pesawat angkat angkut, kelistrikan, pencegahan kebakaran, kesehatan kerja, konstruksi bangunan, lingkungan kerja, sarana K3, operator/teknisi/petugas, perusahaan jasa K3, hingga perancangan bangunan. Kesemuanya memiliki detail teknis yang dituangkan baik dalam Peraturan Menteri, hingga setingkat Direktorat Jenderal.
Namun pasal 15 UU Keselamatan Kerja hanya mengkategorikan pidana atas pengabaian keselamatan kerja sebagai pelanggaran. Hanya dikenakan kurungan 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000 rupiah. Sialnya Undang-undang yang demikian inilah yang masih berlaku hingga era millennium saat ini.
Seringkali,pemerintah beralasan UU 1 Tahun 1970 ini sudah baik sehingga belum memerlukan revisi. Padahal, situasi ketenagakerjaan dan bahaya yang dihadapi pekerja terus berubah. Nuansa monopoli pemerintah untuk menetapkan “Ahli K3” dalam UU ini misalnya, sangat jauh berbeda dengan situasi tripatrit dalam penyelesaian masalah perburuhan. Belum lagi soal ringannya sanksi terhadap pelanggar UU ini dan pasifnya posisi pemerintah dalam pengawasan yang mengandalkan laporan. Dan laporan inilah yang juga menjadi masalah carut-marutnya data yang dipublikasikan Kementerian sampai saat ini.
Butuh Peraturan Kuat
Data Pusdatin Kemenaker (Juni 2017) menyebutkan setidaknya ada 15.170.623 pekerja lebih yang terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dari 398.757 perusahaan terdaftar per Juni 2017. Padahal data BPS Februari 2017 menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada 12 lapangan kerja utama mencapai 124.538.849 orang dengan 16,573,121 bekerja di sektor industri.
Jika diambil data pekerja industri dari BPS (2017), ditambah 39,7 Juta pekerja Pertanian dan Perikanan, 7,2 Juta pekerja konstruksi, 1,4 Juta pekerja pertambangan, 414,8 Ribu pekerja listrik, gas, dan air minum dan 5,7 Juta pekerja transportasi, pergudangan dan komunikasi, mereka inilah yang berpotensi menjadi korban pengabaian kesehatan dan keselamatan kerja.
Tahun 2016 saja terjadi peningkatan 349,4 persen jumlah kematian pekerja dari tahun sebelumnya, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemnaker, Maruli Apul Hasoloan (liputan6.com). Sebanyak 2.382 pekerja yang tewas pada 2016 ini jauh lebih besar dari tahun 2015 yang berjumlah 530 orang. Sumbangan peningkatan jumlah kematian ini 50 persennya berasal dari sektor konstruksi.
Merujuk perhitungan organisasi pekerja internasional (ILO) (2013), dari 100.000 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, 20 diantaranya dalam kondisi sangat fatal. ILO juga pernah mengatakan (2013) bahwa 1 orang pekerja di dunia tewas setiap 15 detik, dan 160 pekerja lainnya menderita sakit akibat kerja.
Disaat Indonesia sedang berkonsentrasi besar dalam bidang konstruksi infrastruktur yang ditandai dengan porsi APBN yang terus diperbesar, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja sudah selayaknya makin diperhatikan. Apalagi pemerintah berniat membangun sentra-sentra industri Indonesia melalui 36 kawasan industri sampai tahun 2035. Tahun 2013-2016 Sebanyak 23 kawasan industri sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 7 diantaranya sudah beroperasi.
Gencarnya pemerintah mendorong pembangunan industri dengan memberi berbagai insentif kemudahan investasi dengan 16 paket ekonomi yang telah dilahirkan, sayangnya masih mengabaikan aturan yang tegas untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja.
Data Kementerian Kenagakerjaan Juni 2017 mengatakan hanya terdapat 1.625 orang tenaga pengawas umum yang 10 persennya berada di pusat, dan 296 tenaga spesialis dan 367 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah inilah yang bertugas mengawasi 398.757 industri (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan), 1 berbanding 207 perusahaan. Sungguh merupakan jumlah yang tidak sebanding dan pastinya akan tidak akan efektif mengawasi apalagi dengan cara yang aktif. Padahal kuasa yang diberikan UU 1 Tahun 2017 kepada pemerintah begitu besar.
Dalam peristiwa ledakan pabrik petasan-kembang api di Kosambi, Tangerang, argumentasi yang digunakan juga serupa dan hampir selalu sama di peristiwa lainnya. Kekurangan tenaga pengawas, ketidakpatuhan perusahaan untuk lapor kondisi tenaga kerja, dan paling apes adalah mengatakan bahwa pekerjalah yang abai terhadap aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Akhirnya, dengan kultur ketimuran, pengusaha “dipaksa” untuk memberikan “uang kerohiman.” Padahal Indonesia adalah negara hukum yang semestinya bisa menetapkannya secara lebih pasti.
Fakta bahwa UU Keselamatan Kerja belum dapat maksimal memberikan kepastian hukum dan keadilan, tenaga pengawas dari kementerian yang minim, makin membesarnya jumlah pekerja dan variatifnya industri harusnya menjadi desakan untuk segera mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan kuat.
Ada dua solusi peraturan yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kondisi ini. Pertama melakukan revisi terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Revisi UU 1/1970 pernah diwacanakan sejak tahun 2000-an dan terus dijadikan wacana oleh Kementerian bidang Tenaga Kerja. Namun belum pernah ada draft revisi UU 1/1970 ini yang dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau bahkan sekedar masuk dalam Rancangan Kerja Program di Kementerian. Tahun 2012 dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar konon revisi UU 1 /1970 ini pernah dikaji untuk dilakukan revisi. Namun entah kemana hasil kajiannya, yang pasti DPR tidak memiliki naskah apapun yang diajukan untuk merevisi Undang-undang yang sudah berusia 47 Tahun.
Memang ada rencana dari Kementerian Hukum dan HaM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memasukkan RUU Bahan Kimia yang diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian periode 2014-2019. RUU ini berkaitan dengan penggunaan Bahan Kimia, Beracun, Berbahaya yang juga disebutkan dalam UU 1/1970. Namun di sisi prakarsa Kementerian Ketenagakerjaan ternyata BPHN hanya mencatat upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengubah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) (yang kini sudah menjadi UU).
Bukan perkara mudah untuk mendesak DPR melakukan pembahasan usulan Undang-undang. Waktu yang dibutuhkan pun tidaklah sebentar. Daftar prolegnas yang ada masih membutuhkan konsentrasi untuk diselesaikan tepat waktu. Akan sulit untuk mengandalkan pembahasan di DPR untuk merubah UU Keselamatan Kerja. Apalagi tidak lama lagi akan memasuki tahun politik yang pasti menyita banyak waktu para anggota DPR.
Jika melihat fakta terus naiknya tren naiknya klaim jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan, 36.453 Kasus (2015), 33.151 Kasus (2016) (per April 2016), belum kunjung masuknya rencana perubahan UU 1/1970, semestinya hal ini dapat dijadikan alasan subjektif presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perppu) tentang keselamatan kerja. Kebutuhan terhadap perlindungan bagi para pekerja merupakan hak yang harus dipenuhi negara.
Negara perlu melindung tenaga kerjanya bukan hanya dari serbuan tenaga kerja asing atau dari pergantian dengan mesin. Tenaga kerja juga perlu di lindungi dalam setiap aktifitas kerjanya. Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengusulkan hal ini kepada presiden sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Pendataan situasi tenaga kerja yang baik, hukum yang tegas untuk melindungi pekerja, dan kepastian dunia usaha melakukan kegiatannya harus ditopang dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang baru. Sesuai dengan konteks zamannya dan masa depan yang akan dihadapi.